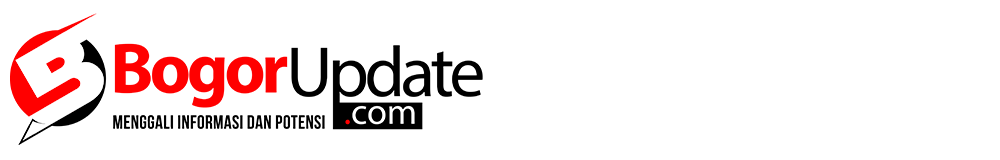Opini, BogorUpdate.com – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi digital, masyarakat dunia, termasuk Indonesia, menghadapi ancaman yang tidak kasat mata namun berdampak besar: brain rot.
Istilah ini merujuk pada kemunduran kemampuan mental dan intelektual seseorang akibat terlalu sering mengonsumsi konten yang remeh, dangkal, tidak penting, dan minim nilai.
Fenomena ini terjadi seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan konsumsi konten daring yang lebih mementingkan hiburan cepat daripada pemikiran yang mendalam.
Istilah brain rot sendiri bukanlah hal baru. Menariknya, frasa ini pertama kali tercatat dalam literatur klasik Walden karya Henry David Thoreau pada tahun 1854.
Dalam karyanya, Thoreau mengkritik kecenderungan masyarakat untuk meninggalkan pemikiran kompleks dan beralih kepada gagasan-gagasan sederhana yang murah dan populer.
Ia menyamakan gejala ini dengan penyakit: “tidakkah ada upaya untuk menyembuhkan kebusukan otak yang telah menyebar luas dan fatal?”
Kritik ini, meski berumur ratusan tahun, justru sangat relevan dengan kondisi saat ini, ketika masyarakat lebih memilih video berdurasi 15 detik ketimbang membaca artikel panjang atau buku bermutu.
Kepopuleran istilah brain rot melonjak drastis di era media sosial dan bahkan dinobatkan sebagai Word of the Year oleh Oxford University setelah proses pemungutan suara yang melibatkan lebih dari 37.000 orang.
Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap kemerosotan intelektual bukan hanya dirasakan oleh segelintir akademisi, tetapi sudah menjadi kesadaran publik secara global.
Di Indonesia, istilah ini mulai diperbincangkan di ruang digital, terutama sebagai bentuk kritik terhadap maraknya konten viral yang cenderung tidak mendidik namun mendominasi perhatian masyarakat.
Di Indonesia, gejala brain rot muncul dalam berbagai bentuk. Salah satu contohnya adalah tren konten TikTok yang berisi tantangan aneh, drama selebriti instan, hingga cuplikan hiburan yang hanya memuaskan rasa ingin tahu sesaat.
Meski tidak semuanya buruk, dominasi konten semacam itu menciptakan kebiasaan konsumsi informasi yang serba cepat, dangkal, dan tanpa refleksi.
Akibatnya, banyak orang mulai kehilangan kemampuan untuk fokus, berpikir kritis, atau mencerna informasi yang lebih kompleks. Inilah yang menjadi inti dari fenomena brain rot.
Faktor penyebab brain rot di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari rendahnya literasi membaca, kurangnya kebiasaan berpikir kritis sejak dini, dan sistem pendidikan yang masih menekankan hafalan.
Ditambah lagi, algoritma media sosial secara aktif mendorong konten yang memicu klik dan emosi sesaat, bukan konten yang membangun wawasan.
Akibatnya, meskipun teknologi memberikan akses pada pengetahuan tak terbatas, yang dikonsumsi justru adalah materi-materi yang mempercepat kemunduran intelektual.
Namun, menyalahkan media sosial sepenuhnya tentu tidak adil. Masalah utamanya terletak pada minimnya kemampuan masyarakat untuk memilah dan mengelola informasi secara bijak.
Di sinilah pentingnya membangun budaya literasi dan keingintahuan intelektual, dimulai dari rumah dan sekolah. Anak-anak perlu dikenalkan pada kegiatan membaca, berdiskusi, dan mengevaluasi informasi sejak dini. Guru dan orang tua juga harus menjadi teladan dalam menyeimbangkan hiburan dan edukasi dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk melawan brain rot, Indonesia membutuhkan pendekatan kolektif. Pemerintah bisa berperan melalui kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pemahaman dan nalar kritis. Lembaga media bisa memperbanyak produksi konten edukatif yang menarik.
Masyarakat sipil bisa memulai gerakan literasi di komunitas. Dan yang paling penting, individu harus menyadari bahwa apa yang kita konsumsi setiap hari, baik itu buku, video, maupun status media sosial, akan membentuk cara berpikir kita di masa depan.
Jika tidak ada upaya serius untuk mengatasi brain rot, maka kemajuan digital hanya akan menjadi ilusi. Di tengah derasnya informasi, masyarakat bisa menjadi lebih mudah tersesat, lebih emosional, dan kurang rasional.
Thoreau sudah memperingatkan sejak abad ke-19, dan kini kita melihat kenyataannya. Pertanyaannya: akankah kita hanya menjadi konsumen pasif dari kebisingan digital, atau bangkit untuk menjadi pembelajar sejati yang mampu berpikir dalam, bernalar tajam, dan bertindak bijak? (Gus)